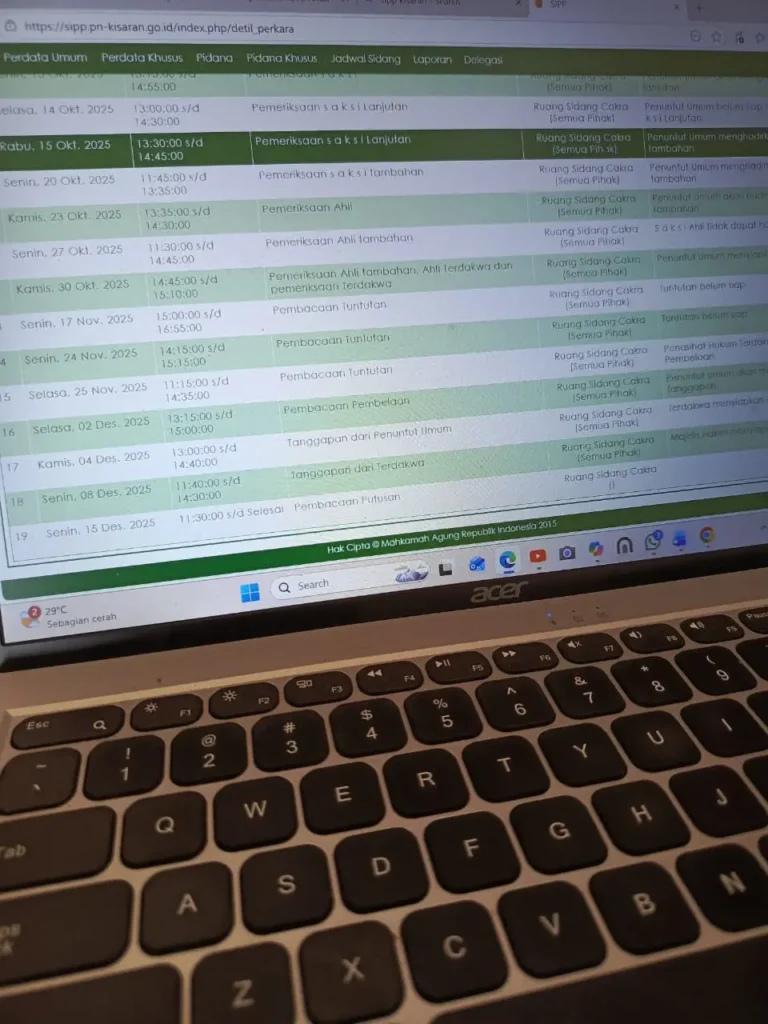Pengantar: Refleksi, Bukan Tuduhan
MEDIA DIALOG NEWS – Tulisan ini bukanlah tuduhan atau pelaporan kasus hukum, melainkan refleksi pribadi atas fenomena pencatutan nama yang kerap terjadi di lapangan. Sebagai jurnalis yang menjunjung etika dan integritas, aku merasa perlu mengangkat isu ini sebagai bentuk edukasi publik. Praktik “menjual kepala” bukan hanya merugikan individu, tapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan profesi. Maka, tulisan ini bertujuan untuk membuka ruang dialog, bukan menghakimi.
“Pencatutan nama dalam transaksi ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Jika dibiarkan, ia akan menjadi budaya gelap yang merusak fondasi etika sosial.” — Dr. Erwin Nasution, SH., MH., pakar hukum pidana dan perlindungan data pribadi
“Jurnalis yang berani mengungkap praktik pencatutan nama, meski dirinya jadi korban, sedang menjalankan fungsi kontrol sosial yang paling mendasar.” — Rika Sari, Redaktur Senior dan penggiat literasi media
Fenomena “Menjual Kepala”
Istilah menjual kepala mungkin terdengar ganjil bagi sebagian orang. Namun di lapangan, praktik ini bukan hal baru. Ia merujuk pada tindakan mencatut nama seseorang—yang bahkan tidak tahu-menahu—untuk didaftarkan sebagai penerima sejumlah “uang pengaman” dari bisnis ilegal. Ironisnya, uang itu tak pernah sampai ke nama yang dicatut. Justru diambil oleh si penjual kepala.
Modusnya beragam. Ada yang terang-terangan mengaku sebagai utusan, lalu meminta uang dengan dalih pengamanan. Ada pula yang mengklaim bisa “mengamankan” orang lain asal diberi sejumlah uang. Dengan bujuk rayu dan narasi meyakinkan, si penjual kepala menipu demi segepok rupiah.
Kemarin, seorang kawan berkata, “Nama Abang laku dijual Rp.5 juta.” Ia tertawa, tapi aku tahu maksudnya serius. Dia melanjutkan, “Di luar sana nama Abang jelek, Bang. Abang katanya terima duit tapi masih terus memberitakan.”
Aku jawab santai, “Biar saja. Orang tahu aku tidak menerima duitnya. Siapa nama orangnya dan dari siapa dia minta duitnya? Biar ku konfirmasi orang yang meminta dan yang diminta.”
Kawanku menyebut beberapa nama. Aku kenal mereka. “Di depan mataku sendiri, Bang, dia menyebut anggota Abang, dan bisa mengamankan abang” ujarnya meyakinkan.
Validasi, Bukan Asumsi
Lalu bagaimana sikapku? Aku belum percaya cakap kawanku kalau belum ada bukti valid. Tapi jika ada pengakuan dari orang yang memberi uang kepada seseorang, barulah aku percaya 100%. Itu pun harus jelas: siapa nama orangnya, berapa jumlah uangnya, untuk alasan apa diberi, kapan, di mana tempatnya, dan siapa saksinya. Paling penting adalah, mengapa dan untuk apa namaku dibawa-bawa dalam transaksi tersebut?
Sebagai jurnalis, aku terbiasa memverifikasi. Tuduhan tanpa bukti hanya akan memperkeruh suasana dan bisa menjadi fitnah. Maka, aku memilih jalan yang lebih panjang: klarifikasi, konfirmasi, dan jika perlu, langkah hukum.
Jerat Hukum bagi Penjual Kepala
Dalam konteks hukum, tindakan mencatut nama orang lain tanpa izin termasuk dalam kategori pemalsuan identitas dan penipuan. Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika seseorang dengan tipu muslihat atau kebohongan memperoleh keuntungan dari orang lain.
Lebih lanjut, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bahwa penggunaan data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya dapat dikenai sanksi administratif dan pidana. Nama seseorang termasuk dalam kategori data pribadi umum, dan pencatutan nama untuk kepentingan transaksi ilegal bisa dianggap sebagai pelanggaran serius.
Dalam praktiknya, pencatutan nama juga melanggar etika sosial dan integritas publik. Apalagi jika dilakukan oleh orang yang dekat dengan pejabat atau pengusaha, maka dampaknya bisa meluas ke ranah kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
Menjaga Nama, Menjaga Marwah
Nama bukan sekadar identitas. Ia adalah marwah, reputasi, dan jejak hidup seseorang. Ketika nama dijual tanpa izin, yang tercoreng bukan hanya citra pribadi, tapi juga kepercayaan publik. Maka, penting bagi kita untuk bersikap tegas terhadap praktik semacam ini.
Sebagai jurnalis dan warga yang menjunjung etika, aku memilih untuk tidak gegabah. Validasi tetap nomor satu. Tapi jika bukti sudah jelas, maka langkah hukum dan klarifikasi publik adalah keniscayaan.
Karena di dunia yang penuh tipu daya, menjaga nama baik bukan sekadar urusan pribadi. Ia adalah benteng terakhir dari integritas yang tak bisa dijual. (**)